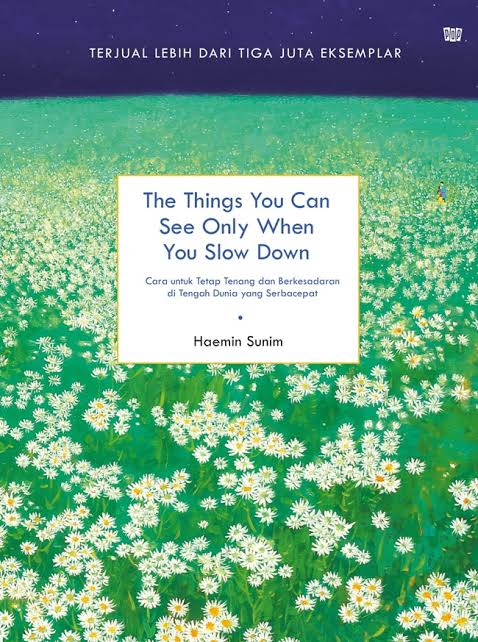Oleh: Allicia Dhea
“Bagaimana cara untuk sembuh?”—pertanyaan ini terus berputar di kepala saya, bersamaan dengan pertanyaan lainnya: Kapan aku akan sembuh? Dua pertanyaan yang datang silih berganti, baik di masa lalu ketika saya menyadari bahwa duka telah menyelimuti hidup hingga menyakiti jiwa saya, maupun di masa kini ketika saya merasa telah menemukan seberkas jawaban. Barangkali masih ada jawaban yang lebih baik dari apa yang saya yakini sekarang, tapi saya tetap mencari, saya tetap belajar.
Berbicara tentang duka, saya pernah—dan mungkin masih—dipenuhi oleh duka, khususnya saat remaja. Rasanya seperti dibanjiri. Saya kehilangan orang-orang yang sangat saya cintai. Jika ditanya seberapa besar duka itu, jawabannya: cukup besar—begitu besar, hingga seorang remaja yang kala itu sedang mencoba memahami konsep cinta akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar sedang jatuh cinta. Saat itu saya memahami, ternyata jumlah cinta yang kita miliki sebanding dengan dalamnya duka yang kita alami. Semakin besar cinta, semakin besar pula ombak dukanya.
Di tengah lautan duka yang luas itu, saya pun—seperti manusia kebanyakan—memburu kebahagiaan. Saya serupa bajak laut yang berharap menemukan harta karun, berbekal peta yang entah dibuat siapa. Keyakinan saya saat itu sederhana: jika bisa melewati lautan duka, maka di ujung sana, kebahagiaan menanti. Maka, strategi saya: tempuh dulu dukanya, baru dapat bahagiannya.
Mungkin itulah alasan saya begitu lapar akan kesembuhan. Saya merindukan bahagia, sebagaimana orang dewasa merindukan masa kecil yang damai dan naif. Dalam pikiran saya, kebahagiaan itu harus sempurna: penuh, besar, mengenyangkan, dan datang sebagai hadiah setelah segala duka menguap. Seperti pelangi setelah hujan. Mungkin saya terlalu sering membaca kutipan “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian” di buku pelajaran. Kutipan yang seharusnya tak perlu terlalu sering diulang-ulang.
Sampai suatu hari, tangan saya meraih buku Haemin Sunim, The Things You Can See Only When You Slow Down. Awalnya saya skeptis—seorang ahli agama menulis soal hidup yang tenang? Tapi justru di sanalah, saya menemukan jawaban atas dua pertanyaan yang selama ini menggema di kepala. Seperti yang ia tulis (2020:44):
“Saat kita berusaha memahami sesuatu, cara paling efektif adalah membuang jauh-jauh prasangka dan mengamati dalam diam, sehingga objek yang kita amati akan menunjukkan apa yang seharusnya kita pahami.”
Lalu, bagaimana cara sembuh? Dan kapan aku sembuh?
Jawabannya muncul dengan lembut dan sederhana di halaman awal, bab pertama yang berjudul “Istirahat” (2020:17):
“Untuk membersihkan sisa makanan yang lengket di wajan, tuangkan saja air ke dalam wajan dan menunggu. Setelah beberapa saat, makanan itu akan lepas dengan sendirinya. Jangan berusaha menyembuhkan luka kita. Tuangkan saja sedikit waktu ke dalam hati kita dan menunggu. Ketika kita merasa siap, luka itu akan sembuh dengan sendirinya.”
Di situlah saya tersadar: jawaban itu juga sekaligus permasalahan saya. Saya terlalu haus akan kesembuhan, terlalu lapar akan kebahagiaan. Saya terus berlari dalam maraton hidup, padahal hidup ini bukanlah lomba. Saya ingin sembuh dengan cepat, karena saya pikir kesembuhan total adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan utuh.
Padahal kenyataannya, tidak.
Duka tidak selamanya tinggal. Ia datang dan pergi, meninggalkan sela-sela kecil bagi kebahagiaan untuk menyelinap masuk. Saya hanya tak menyadarinya—atau mungkin menolaknya, karena terlalu fokus mencari kebahagiaan yang sempurna.
Padahal, kebahagiaan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana: bangun pagi tanpa sakit pinggang, makan makanan enak, mendapat diskon dari produk incaran. Tapi saya sibuk mengejar versi ideal kebahagiaan, yang sempurna, besar, dan dramatis. Lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk sempurna, sesempurna apa pun kita mencoba.
Lewat kalimat-kalimatnya yang hangat dan bebas penghakiman, Haemin Sunim seolah menawarkan segelas air dingin di tengah lelahnya perjalanan saya. Ia mengajak saya berhenti sejenak, melambat, menarik napas panjang. Sesuatu yang sangat asing bagi pikiran saya yang bising. Sesuatu yang terasa ganjil di tengah dunia yang berputar cepat—30 km per detik, kata Simon Lock dari School of Earth Sciences, University of Bristol.
Dan saya pun beristirahat.
Istirahat yang panjang dan layak. Untuk pertama kalinya, saya bisa menarik napas dalam hingga paru-paru terasa penuh—bukan karena sistem tubuh memaksa, tapi karena jiwa saya memang ingin bernapas. Saya kembali merasakan nikmatnya makanan, bahkan mampu membedakan ayam geprek yang sambalnya pakai micin atau tidak. Lebih dari itu, saya—yang semula mengira membenci manusia—mulai menyukai interaksi. Saya menemukan energi dalam pertemuan: teman-teman seperjuangan di kampus, anggota keluarga yang selalu menghormati saya, keponakan lucu yang saya panggil kiyomi (cutie), dan orang-orang baik lainnya.
Suatu hari, saat merayakan kelulusan seorang sahabat yang sangat berarti bagi saya, saya menulis:
“Tadinya kukira cinta itu menyakitkan. Ternyata, cinta jugalah yang menyembuhkan.”
Kini saya hidup jauh lebih baik, setelah saya belajar menuangkan waktu ke dalam “wajan” kotor penuh duka saya. Masa-masa duka itu perlahan menguap, bersamaan dengan rasa lapar dan haus yang dulu menggerogoti. Seperti wajan yang perlahan bersih, saya pun perlahan sembuh.
Referensi
- Haemin Sunim. (2020). The Things You Can See When You Slow Down (Terjemahan). Jakarta: Gramedia.
- Space.com. (2025). How Fast is Earth Moving. Diakses dari https://www.space.com/33527-how-fast-is-earth-moving.html
link pembelian buku: https://s.shopee.co.id/6Ku0LjKVjF
Editor: Tim Ngajiliterasi